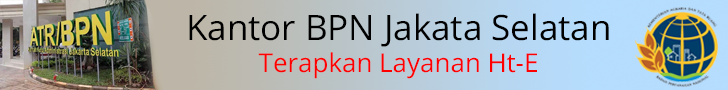Jakarta, ToeNTAS.com,- Dalam beberapa bulan ini, publik terus disuguhi dengan pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Jombang. Kasus ini tentunya bukan yang pertama di Indonesia, tapi merupakan kasus yang terjadi untuk kesekian kalinya, di lembaga yang seyogianya berperan untuk mempersiapkan generasi Indonesia menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
Bila kita melihat pada penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan, prosesnya sangat kompleks dan panjang. Ini pula yang terjadi pada penanganan kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang. Fakta ini rupanya menggelitik publik untuk menelisik lebih dalam, kira-kira ada apakah gerangan, sehingga penanganan sebuah kasus dapat mengendap dan berkepanjangan.
Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengulas tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus yang dilakukan, tetapi titik fokus pembahasannya akan menggali tentang berbagai faktor intangible yang berdampak signifikan terhadap keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan seksual.
Menjaga Marwah
Upaya penanganan kasus kekerasan seksual diakui atau tidak telah terperangkap dalam dialektika upaya menjaga marwah demi mempertahankan dignitas sebuah kehormatan. Pola ini pula yang terjadi dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, yang menyebabkan penanganan kasus menjadi lamban, rumit, dan tidak berkesudahan. Padahal, kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Jombang pada 29 Oktober 2019.
Pesantren Shiddiqiyyah merupakan sebuah pesantren besar dan ternama di kabupaten yang dijuluki kota seribu santri. Pengasuhnya bernama KH Muchammad Muchtar Mu’thi, yang dikenal sebagai seorang mursyid atau guru tarekat Thoriqoh Shiddiqiyyah bagi masyarakat sejak tahun 1959 hingga sekarang. Kegiatan yang dilakukan utama di pesantren ini adalah bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan ekonomi. Sehingga tak heran, pesantren ini menjadi ikon kebanggaan bagi masyarakat Jombang.
Kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan Shiddiqiyyah ini telah ditangani lebih dari dua tahun, dan dalam prosesnya kerap menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama yang mendasar adalah adanya penolakan untuk mengakui tentang kasus ini karena pelaku berasal dari entitas yang dihormati dan merupakan simbol dignitas dari masyarakat sekitar. Salah satu pola yang digunakan untuk menjaga dignitas tersebut adalah dengan melakukan berbagai upaya ‘pengingkaran’ terhadap kasus kekerasan yang dilakukan.
Menariknya, upaya pengingkaran tidak hanya dilakukan oleh pemilik pesantren yang merupakan keluarga pelaku, tapi juga menjadi perjuangan para pengikut setia dari kalangan internal yang memiliki hubungan langsung dengan pesantren. Selain itu, perjuangan ‘menjaga marwah’ ini juga didukung penuh oleh masyarakat umum yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pesantren (pihak eksternal), baik secara individu maupun kelembagaan yang dilakukan secara masif dan struktural, sebagai upaya melindungi nama baik sebuah entitas yang dibanggakan.
Celah ini rupanya dilihat dengan jeli oleh si pelak, sebagai sebuah peluang yang digunakan untuk memobilisasi masa (pengikut atau kelompok yang loyal) menjadi tameng perlindungan dari tuduhan pelanggaran yang ia lakukan. Selain itu, karena tersangka memiliki pengaruh yang kuat, selama proses penanganan kasus, terdapat berbagai intervensi yang sangat kuat dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalangi proses fact finding, dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan kekerasan, demi tertutupinya tindak kekerasan yang dilakukan.
Salah satu contoh aksi yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan penganiayaan serta ancaman kekerasan pada seorang Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang tergabung dalam Front Santri Melawan Kekerasan Seksual (FSMKS) pada 9 Mei 2021. Peristiwa penganiayaan tersebut merupakan salah satu akibat yang harus dituai dari penundaan terhadap penanganan kasus yang berlarut-larut serta ketidakpastian hukum, impunitas pelaku, dan risiko pelanggaran hukum yang berkelanjutan.
Berbagai situasi permisif yang terstruktur tersebut, juga dimanfaatkan secara cerdas oleh tersangka dan suporternya untuk membelokkan kasus ini menjadi sebuah bentuk tuduhan terhadap pencemaran nama baik bagi pondok pesantren. Lambatnya proses hukum yang dilakukan juga dimanfaatkan kembali oleh pelaku untuk mengajukan permohonan pra-peradilan.
Potret Kontestasi
Untuk memahami potret kontestasi yang terjadi, dalam proses penanganan kasus yang dilakukan, saya mencoba memaparkan analisis ke dalam sebuah analogi yang sederhana, yang dapat diibaratkan seperti dua kelompok yang saling berseteru untuk mendapatkan legitimasi publik terkait suatu hal, dan bagaimana upaya, dengan berbagai pendekatan yang berbeda tersebut, dimaknai oleh publik secara berbeda.
Bagi kelompok pertama, perjuangan yang mereka lakukan dipandang untuk melindungi marwah sebuah komunitas. Marwah dipandang sebagai puncak tertinggi kehormatan sebuah entitas yang harus diperjuangkan. Perjuangan tersebut dipandang sebagai bentuk pemenuhan kepentingan orang banyak, bukan individu ataupun golongan.
Sedangkan, bagi kelompok yang kedua, perjuangan untuk memenuhi hak korban, dipandang sebagai sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan personal atau kelompok tertentu saja. Yang diperjuangkan juga hajat hidupnya perempuan (atau anak perempuan) yang notabenenya merupakan kelompok yang dipinggirkan.
Selain itu, kekerasan seksual dalam pandangan masyarakat secara umum hanya dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran etika, bukan sebagai bentuk pelanggaran hak azasi manusia yang fundamental, sehingga penyelesaiannya pun dapat dilakukan hanya dengan damai. Lebih jauh, dalam kekerasan seksual, korban yang mayoritasnya perempuan (dan anak perempuan) dipandang sebagai objek seksual, sehingga dalam masyarakat berkembang pula budaya permisif yang menganggap wajar (membiarkan) bila perempuan (atau anak perempuan) patutlah menjadi korban.
Dalam skenario di atas, tentu secara kasat mata terlihat jelas, pihak mana yang akan menjadi pemenang. Tentu saja, kelompok pertama yang mempunyai misi memperjuangkan harkat dan martabat khalayak ramai, bukan kelompok kedua, yang hanya memperjuangkan hak segelintir orang.
Pola inilah yang dijalankan dalam berbagai penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk penanganan kasus kekerasan di pesantren Shiddiqiyyah Jombang. Mirisnya, dalam banyak kasus ditemukan fakta yang menunjukkan bila upaya menjaga marwah tersebut, secara nyata telah memasung upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban.
Oleh karena itu, belajar dari kasus ini dan berbagai penanganan kasus kekerasan seksual lainnya yang terus terjadi di negeri ini, membuka mata kita betapa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi harapan besar bagi perlindungan dan pemenuhan hak korban. Sehingga implementasi dari UU TPKS ini harus terus diperkuat dan ditegakkan sebagai upaya yang fundamental dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyintas kekerasan. (d.c/Endah)